Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi di berbagai bidang, termasuk dalam dunia pemasaran dan penamaan merek. Di Indonesia, penggunaan istilah bahasa Inggris dalam penamaan merek semakin marak sebagai strategi untuk menarik perhatian konsumen dan memberikan kesan modern serta internasional. Namun, fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana makna istilah asing tersebut dipahami oleh masyarakat dengan beragam latar belakang bahasa dan budaya.
Dalam konteks ini, filsafat ilmu dan filsafat bahasa, khususnya teori Ludwig Wittgenstein, memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika makna dan komunikasi merek. Esai ini akan membahas bagaimana konsep language games dan meaning as use dari Wittgenstein dapat menjelaskan fenomena penggunaan istilah bahasa Inggris dalam merek di Indonesia, serta implikasinya terhadap validitas dan efektivitas komunikasi pemasaran.
Penggunaan bahasa Inggris dalam penamaan merek di Indonesia bukan hal baru. Merek-merek seperti “AirAsia,” “Zoom,” “Facebook,” dan produk seperti “Smartfren” atau “Indomie Mi Goreng Spicy” menunjukkan bagaimana bahasa Inggris dipilih untuk memberikan kesan modern, profesional, dan global. Menurut Crystal (2003), bahasa Inggris sebagai lingua franca global telah menjadi bahasa dominan dalam komunikasi bisnis dan teknologi, sehingga tidak mengherankan jika istilah-istilah bahasa Inggris merambah ke ranah merek dan pemasaran.
Namun, penggunaan istilah asing ini tidak selalu mudah diterima atau dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagian konsumen mungkin hanya mengenal istilah tersebut sebagai label tanpa memahami makna atau konteks aslinya. Hal ini menimbulkan tantangan komunikasi yang berkaitan dengan bagaimana makna sebuah istilah dibentuk dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.
Ludwig Wittgenstein, dalam karya monumentalnya Philosophical Investigations (1953), mengkritik pandangan tradisional bahwa makna kata adalah sesuatu yang tetap dan dapat dijelaskan secara definitif melalui definisi kamus. Sebaliknya, Wittgenstein menegaskan bahwa makna sebuah kata bergantung pada penggunaannya dalam konteks sosial tertentu, yang ia sebut sebagai language games (permainan bahasa). Konsep ini menekankan bahwa bahasa adalah aktivitas sosial yang maknanya terbentuk melalui aturan dan praktik yang berlaku dalam komunitas bahasa tertentu.
Menurut Wittgenstein, “makna adalah penggunaan kata dalam bahasa” (meaning as use). Ini berarti bahwa makna sebuah istilah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kata tersebut digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam konteks merek, istilah bahasa Inggris yang digunakan bukan hanya sekadar label, tetapi bagian dari praktik komunikasi yang melibatkan produsen, konsumen, dan konteks budaya mereka.
Misalnya, kata “Zoom” dalam bahasa Inggris secara literal berarti “bergerak cepat” atau “memperbesar.” Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia saat pandemi COVID-19, “Zoom” lebih dikenal sebagai nama aplikasi video conference yang menjadi bagian penting dari aktivitas belajar dan bekerja jarak jauh. Makna kata ini telah bergeser dan berkembang sesuai dengan penggunaan sosialnya, sesuai dengan teori Wittgenstein.
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman makna istilah asing dalam merek sangat bergantung pada language games yang dimainkan oleh konsumen dan produsen dalam konteks budaya dan sosial mereka. Jika istilah tersebut digunakan dalam konteks yang tidak sesuai atau tidak dipahami oleh audiens, maka komunikasi dapat gagal atau menimbulkan kesalahpahaman.
Dari perspektif filsafat ilmu, komunikasi merek harus memenuhi prinsip validitas dan efektivitas agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan berdampak. Validitas dalam konteks ini berarti bahwa pesan merek harus benar-benar mencerminkan identitas dan nilai produk, serta dapat dipahami oleh audiens secara tepat. Efektivitas berarti pesan tersebut mampu memengaruhi persepsi dan perilaku konsumen sesuai tujuan pemasaran. Penggunaan istilah bahasa Inggris dalam merek harus mempertimbangkan konteks budaya dan kemampuan bahasa audiens agar komunikasi berjalan efektif. Jika istilah asing digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan budaya, maka pesan yang disampaikan bisa menjadi tidak valid atau tidak efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Wittgenstein bahwa makna bergantung pada penggunaan dalam konteks tertentu.
Misalnya, merek “Indomie Mi Goreng Spicy” menggabungkan bahasa Indonesia dan Inggris. Kata “Spicy” memberikan kesan rasa pedas yang menarik konsumen, meskipun kata tersebut adalah bahasa Inggris. Penggunaan kata ini efektif karena banyak konsumen Indonesia sudah familiar dengan istilah tersebut dalam konteks makanan pedas, sehingga maknanya jelas dan sesuai dengan language game yang berlaku. Sebaliknya, jika sebuah merek menggunakan istilah bahasa Inggris yang terlalu teknis atau asing tanpa penyesuaian konteks, maka konsumen mungkin tidak memahami makna yang dimaksud, sehingga komunikasi pemasaran menjadi kurang efektif.
Sebagai contoh, merek “AirAsia” menggunakan bahasa Inggris untuk menonjolkan citra internasional dan kemudahan akses penerbangan. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama ini mungkin hanya dianggap sebagai nama unik tanpa makna khusus, tetapi dalam konteks pasar penerbangan internasional, nama ini efektif sebagai identitas merek global. Merek “Zoom” menjadi sangat populer selama pandemi sebagai aplikasi video conference. Istilah ini kini melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, meskipun makna asli kata tersebut mungkin tidak dipahami secara mendalam. Ini menunjukkan bagaimana makna istilah berkembang melalui penggunaan sosial, sesuai dengan teori Wittgenstein.
Dengan demikian, penggunaan istilah bahasa Inggris dalam penamaan merek di Indonesia merupakan fenomena yang mencerminkan dinamika komunikasi dalam masyarakat multibahasa dan multikultural. Dengan mengacu pada teori Ludwig Wittgenstein, khususnya konsep language games dan meaning as use, kita dapat memahami bahwa makna istilah asing dalam merek terbentuk dan berkembang melalui praktik sosial dan konteks budaya konsumen.
Sementara itu, filsafat ilmu menekankan pentingnya validitas dan efektivitas komunikasi agar pesan merek dapat diterima dan berdampak. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Inggris dalam merek harus disesuaikan dengan konteks dan kemampuan bahasa audiens agar dapat menjembatani produsen dan konsumen secara optimal. Sehingga, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medium yang dinamis dan kontekstual dalam membangun makna dan pengetahuan, yang sangat penting dalam strategi pemasaran dan pengembangan ilmu komunikasi di Indonesia.
Daftar Bacaan relevan
Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge University Press.
Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. Blackwell Publishing.
Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Harvard University Press.
Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press.









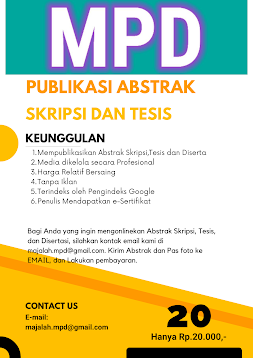









0 Komentar
Silakan tinggalkan komentar Anda