 |
| Suasana Akademis Perkuliahan Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan |
Dr. Icol Dianto, S.Sos.I., M.Kom.I
Dosen Tetap Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
BICARA mengenai perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, saya selalu merasa bahwa perjalanan ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan umat untuk memperkuat dakwah di tengah-tengah perubahan masyarakat. Dulu, dakwah lebih banyak dilakukan dengan cara-cara sederhana: pengajian di surau atau masjid, berkumpul di majelis taklim, dan ceramah-ceramah yang sifatnya langsung. Tapi seiring waktu, perubahan sosial, budaya, dan apalagi teknologi komunikasi, membuat cara masyarakat menerima dan menyebarkan informasi juga berubah. Mau tidak mau, dakwah juga harus ikut beradaptasi. Dari sinilah muncul kebutuhan agar dakwah tidak lagi dilakukan secara tradisional semata, melainkan juga lewat pendekatan yang lebih ilmiah, profesional, dan tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman. Karena itulah ilmu dakwah kemudian berkembang di perguruan tinggi Islam dan melahirkan berbagai konsentrasi. Salah satunya adalah Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), yang memang dirancang untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan teori dan praktik komunikasi modern.
Lahirnya Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam sendiri adalah bentuk jawaban dari tantangan global, terutama di era digital sekarang. Bayangkan, arus informasi begitu deras, budaya populer masuk tanpa batas, dan media sosial jadi ruang utama interaksi masyarakat. Kalau dakwah masih pakai cara-cara lama saja, tentu akan ketinggalan. Karena itu, pesan-pesan Islam hari ini perlu hadir juga lewat media massa, teknologi informasi, dan platform digital agar bisa sampai kepada audiens yang lebih luas. Nah, di titik inilah KPI punya peran penting: menyiapkan generasi Muslim yang bukan hanya pandai berdakwah, tapi juga punya keterampilan komunikasi, penyiaran, bahkan literasi media.
Saya melihat ada urgensi besar dalam pengembangan prodi KPI ini. Tidak cukup lagi kalau lulusannya hanya disiapkan jadi muballigh. Mereka juga harus bisa berkiprah sebagai peneliti, akademisi, jurnalis, produser media, bahkan komunikator publik yang tetap menjunjung tinggi etika Islam. Dengan begitu, wajah dakwah kita bisa tampil lebih ramah, inklusif, dan sesuai dengan semangat rahmatan lil ‘alamin. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, multikultural, jadi komunikasi Islam yang menjadi basis ilmu prodi KPI bisa jadi sarana untuk membangun dialog sosial, memperkuat moderasi beragama, dan menjaga kerukunan.
Di sisi lain, pengembangan Prodi KPI juga punya nilai strategis untuk bangsa. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya modal besar untuk menjadi pusat kajian komunikasi Islam yang diakui di level internasional. Bayangkan kalau kita bisa melahirkan pemikir, peneliti, dan praktisi dakwah yang bukan hanya berkiprah di dalam negeri, tapi juga berkontribusi dalam percaturan peradaban Islam global. Tentu saja, semua itu dilakukan tanpa meninggalkan akar nilai-nilai lokal dan tradisi keislaman khas Nusantara.
Menariknya lagi, pengembangan Prodi KPI sekarang juga dikaitkan dengan kebutuhan paradigma baru yang lebih holistik, yaitu paradigma teoantropoekosentris. Cara pandang ini menggabungkan tiga dimensi sekaligus: teosentris (menjadikan Tuhan sebagai pusat nilai dan tujuan), antroposentris (menempatkan manusia sebagai agen komunikasi dan peradaban), dan ekosentris (mengakui alam sebagai ciptaan Tuhan yang bernilai dan harus dijaga). Paradigma ini penting sekali, karena dakwah Islam bukan cuma soal relasi manusia dengan Tuhan, tapi juga mencakup tanggung jawab manusia terhadap sesamanya, sekaligus kepedulian pada lingkungan. Kalau paradigma ini benar-benar diterapkan dalam pembelajaran Prodi KPI, saya yakin lulusan yang lahir tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga punya kesadaran spiritual, kepekaan sosial, dan kepedulian ekologis.
Kalau kita runut sejarahnya, memang ada tiga kerangka besar yang melatarbelakangi lahirnya paradigma ini: teosentris, antroposentris, dan ekosentris. Paradigma teosentris muncul dari tradisi religius yang menempatkan Tuhan sebagai pusat kosmos sekaligus sumber pengetahuan. Dalam tradisi pendidikan Islam, bahwa tujuan pendidikan harus berlandaskan “taksonomi transenden,” yang mengklasifikasikan nilai ilahiyah, insaniyah, dan kawniyah sebagai basis epistemologi. Sejalan dengan itu, tafsir ekologis juga berkembang, yang melihat bahwa tindakan ekologis pada hakikatnya adalah bentuk iman dan pengakuan terhadap Tuhan sebagai pemelihara semesta. Lalu ada tafsir mengenai konsep khalifah, yang menekankan bahwa manusia dipanggil bukan untuk mengeksploitasi, melainkan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Kemudian muncul paradigma antroposentris, yang lahir bersamaan dengan modernitas dan humanisme. Di sini manusia ditempatkan sebagai pusat nilai, bahkan pusat jagat raya. Sayangnya, pandangan ini melahirkan kecenderungan eksploitasi terhadap alam. Beberapa penelitian memperlihatkan bagaimana antroposentrisme dilegitimasi dalam eksploitasi sumber daya alam. Kritik juga datang dari penelitian-penelitian etika lingkungan yang menunjukkan bahwa antroposentrisme menjadi akar krisis ekologi modern. Lalu lahirlah paradigma ekosentris sebagai koreksi terhadap kegagalan antroposentrisme. Di sini alam dianggap punya nilai intrinsik, bukan sekadar alat bagi manusia. Beberapa akademisi memperkenalkan paradigma tafsir ekologi, sedangkan yang lain berbicara tentang etika animalitas yang menolak diskriminasi terhadap hewan. Bahkan lebih jauh lagi, para peneliti menawarkan tafsir “zoosemiotika sastra” yang menempatkan hewan bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek moral. Semua ini menunjukkan pergeseran dari antroposentris ke ekosentris.
Manusia adalah makhluk pedagogis, dididik sekaligus mendidik. Tapi martabat itu hanya bisa dicapai bila pengetahuan dipadukan dengan iman dan amal saleh. Dari sana kita bisa melihat bahwa ketiga paradigma—teosentris, antroposentris, dan ekosentris—sebenarnya saling terkait dan membentuk dialektika baru dalam pemikiran kontemporer.
Nah, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran KPI? Menurut saya, ada beberapa hal penting. Pertama, kurikulum dirancang bukan hanya menekankan aspek teori dan keterampilan komunikasi, tetapi juga ditopang oleh nilai ilahiah, perhatian terhadap manusia, serta kesadaran ekologis. Kedua, metode pembelajaran perlu memadukan teori komunikasi modern dengan etika Islam, sekaligus diskusi kritis tentang peran manusia dan tanggung jawab ekologis. Ketiga, mahasiswa KPI memang dibekali dengan kompetensi komunikasi, dakwah, dan media. Namun, dalam perspektif teoantropoekosentris, mereka juga harus punya kesadaran spiritual, kepekaan sosial, dan kepedulian ekologis. Keempat, penelitian dan pengabdian masyarakat diarahkan untuk menghasilkan karya yang solutif, inovatif, dan bermanfaat, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi kelestarian lingkungan.
Kalau dikaitkan dengan kondisi global, paradigma ini terasa semakin relevan. Kita tahu bahwa arus informasi begitu bebas, budaya populer makin mendominasi, bahkan krisis lingkungan jadi masalah serius. Paradigma teoantropoekosentris hadir sebagai solusi: meneguhkan nilai spiritual, menjaga relevansi kemanusiaan, dan mengembangkan etika lingkungan. Dengan begitu, komunikasi Islam bukan sekadar media dakwah, melainkan juga bisa menjadi gerakan peradaban yang holistik.
Pada akhirnya, saya melihat bahwa paradigma teoantropoekosentris dalam pembelajaran KPI memberi arah yang jelas untuk pengembangan ilmu komunikasi Islam. Lulusan yang dihasilkan bukan hanya unggul secara akademis, tapi juga mampu bersaing di level internasional dengan komitmen kuat pada nilai ilahiah, kemaslahatan manusia, dan kelestarian alam. Inilah wajah dakwah Islam masa depan yang kita cita-citakan: intelektual, profesional, dan berparadigma rahmatan lil ‘alamin.








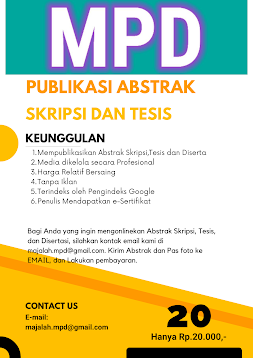









0 Komentar
Silakan tinggalkan komentar Anda