Pendahuluan
Istiqomah di jalan dakwah merupakan sikap konsisten dari seorang muslim untuk mengemban amanah sebagai penyampai risalah Ketuhanan. Tugas mulia itu, dakwah, merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW kepada setiap muslim sesuai dengan kesanggupannya. Dalam konteks agama Islam, Al-Quran menjelaskan bahwa dakwah adalah upaya untuk mengajak manusia menuju jalan kebaikan, terutama dalam QS. Ali Imran: 104, dakwah mengandung tiga aspek utama, yaitu:
- Mengajak kepada kebaikan (al-khayr) – menyampaikan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan.
- Memerintahkan kepada yang makruf (al-ma’ruf) – mendorong perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan disepakati sebagai baik oleh masyarakat.
- Mencegah dari kemungkaran (al-munkar) – menolak dan mencegah perilaku atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebohongan, korupsi, atau kekerasan.
Di sisi lain, setiap muslim dituntut untuk istiqomah dalam berdakwah. Kecaman jika tidak konsisten, Allah sebut kita sebagai orang-orang yang tidak menjalankan risalah yang telah disampaikan kepada kita, melalui Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih jauh, Allah peringatkan kita bahwa:
1. Perbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain
Surah Al-Baqarah ayat 44, berbunyi:
أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
Ata'murūnan-nāsa bil-birri wa tansauna anfusakum wa antum tatlūnal-kitāba, afalā ta'qilūn.
“Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab? Tidakkah kamu berpikir?"
Ayat ini dulunya adalah teguran Allah kepada Bani Israil, namun dalam konteks ayat lebih luas, ayat ini juga menjadi peringatan umum kepada semua orang yang berdakwah atau menyeru kepada kebaikan. Ayat ini mengajarkan bahwa konsistensi antara ucapan dan perbuatan sangat penting, terutama bagi orang yang mengajak kepada kebaikan. Tidak pantas seseorang menyuruh orang lain berbuat baik, namun ia sendiri mengabaikannya.
2. Selaras ucapan dengan perbuatan
يَـٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا
تَفْعَلُونَ
Yā ayyuhallażīna āmanụ
lima taqụlụna mā lā taf‘alụn.
Kabura maqtan ‘indallāhi an taqụlụ mā lā taf‘alụn.
“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.”
Surah Ash-Shaff ayat 2–3 menjadi peringatan tegas kepada para pendakwah atau siapa pun yang menyeru kepada kebaikan agar menjadi pribadi yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Jangan menjadi lilin yang menerangi orang lain, tetapi membakar diri sendiri karena ingkar pada apa yang diajarkannya.
Atas dasar itulah, seseorang yang telah memilih Islam sebagai agamanya wajib untuk beristiqomah di jalan kebaikan. Lebih lagi bagi seseorang yang dijuluki ulama, kiyai, ustad, dan panggilan mulia lainnya, mesti memiliki keistiqomahan yang mantap.
Peerihal istiqomah, Allah berfirman dalam QS. Al-Ahqaf ayat 13,
إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
Innallażīna qālụ rabbunallāhu ṡummastaqāmụ fa lā khaufun 'alaihim wa lā hum yaḥzanụn
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.
Definisi Istiqomah
Secara etimologi, kata istiqomah berasal dari bahasa Arab: اِسْتِقَامَ - يَسْتَقِيْمُ - اِسْتِقَامَةً, yang merupakan turunan dari kata dasar قَامَ – يَقُوْمُ – قِيَامًا, yang berarti “berdiri tegak” atau “tegak lurus”. Dalam pengertian bahasa, istiqomah memiliki makna lurus, teguh, dan tetap berada di atas jalan yang benar. Ia juga mengandung arti konsisten dalam sikap atau perbuatan tanpa menyimpang. Dalam Kamus Lisān al-‘Arab, dijelaskan bahwa istiqomah berarti “berada di atas jalan yang lurus dan tidak menyimpang ke kanan atau kiri,” menunjukkan makna keteguhan dan kelurusan dalam menjalani prinsip hidup.
Beberapa mufasir klasik dan kontemporer memberikan penafsiran mendalam terhadap konsep istiqomah, khususnya ketika menafsirkan ayat:
إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ .
Arab-Latin: Innallażīna qālụ rabbunallāhu ṡummastaqāmụ tatanazzalu 'alaihimul-malā`ikatu allā takhāfụ wa lā taḥzanụ wa absyirụ bil-jannatillatī kuntum tụ'adụn
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". QS. Al-Fussilat: 30
Imam al-Thabari, Dalam Tafsir al-Thabari, beliau menafsirkan istiqomah sebagai: “Tetap teguh di atas keimanan kepada Allah dan tidak menyimpang darinya, baik dalam ucapan maupun amal.”
Imam al-Qurtubi, dalam Tafsir al-Qurtubi, istiqomah dijelaskan: “Berpegang teguh di atas tauhid, menjalankan ketaatan, dan meninggalkan kemaksiatan secara terus-menerus.”
Imam Ibn Katsir, dalam Tafsir Ibn Katsir: “Mereka menetapkan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, kemudian mereka istiqomah di atas jalan-Nya, yakni tidak berpaling kepada selain-Nya.”
Imam Fakhruddin al-Razi, dalam Mafatih al-Ghayb, al-Razi menyatakan bahwa istiqomah: “Adalah bentuk sempurna dari ketaatan secara terus-menerus tanpa menoleh ke belakang.”
Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa Istiqomah secara bahasa berarti tetap teguh dan lurus. Sementara itu, menurut para mufasir, istiqomah adalah konsistensi dalam iman dan amal, teguh di atas kebenaran, tidak menyimpang dari tauhid, dan terus menerus dalam ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat.
Pengembaraan Dalam Mencari Tuhan
Aguste Comte, filsuf dan sekaligus sosiolog dari Perancis, dalam teorinya Tiga Tahap Perkembangan Pemikiran Manusia (Three Stages of Human Knowledge), Comte membagi perkembangan pemikiran manusia menjadi tiga tahap:
- Tahap Teologis (Religius)
- Manusia menjelaskan fenomena alam dan kehidupan dengan keyakinan kepada kekuatan supranatural atau dewa-dewi.
- Agama memenuhi kebutuhan akan penjelasan terhadap hal-hal yang belum dipahami secara rasional.
- Ini adalah bentuk awal dan paling primitif dari pengetahuan.
- Tahap Metafisik
- Manusia mulai mengganti kepercayaan supranatural dengan abstraksi atau konsep-konsep filosofis (seperti “hukum alam”).
- Agama mulai digantikan oleh filsafat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan besar.
- Tahap Positif (Ilmiah)
- Manusia hanya menerima pengetahuan yang bisa dibuktikan secara ilmiah (empiris).
- Agama tidak lagi dianggap sebagai sumber pengetahuan ilmiah, tapi lebih sebagai bagian dari sejarah pemikiran manusia.
Bagi Comte:
- Agama memiliki fungsi sosial penting di masa lalu sebagai bentuk pengatur moral dan keteraturan masyarakat.
- Namun, dalam pandangan positivisnya, agama tidak lagi diperlukan sebagai sumber kebenaran dalam era modern. Ia harus digantikan oleh ilmu pengetahuan.
- Meski begitu, Comte tidak menolak struktur sosial agama. Ia bahkan pernah menggagas “agama kemanusiaan” (religion of humanity), di mana manusia dan kemanusiaan dijadikan objek pengabdian, bukan Tuhan.
Berbeda dengan pandangan positivistik seperti yang dikemukakan oleh Auguste Comte, Islam memandang bahwa kebutuhan manusia kepada Tuhan (Allah) bersifat fitri dan terus-menerus, tidak terbatas pada satu tahap perkembangan saja. Dalam perspektif Islam, tahapan manusia dalam menjalin hubungan dengan Tuhan dapat dibagi menjadi beberapa fase. Tahap pertama adalah masa belajar dan menerima, yang berlangsung sejak lahir hingga usia sekitar 12 tahun, yaitu sejak dari ayunan hingga baligh. Pada tahap ini, anak-anak menyerap nilai-nilai tauhid, iman, dan ajaran agama dari lingkungan keluarga dan pendidikan dasar. Tahap kedua adalah masa pencarian kebenaran, yang dimulai ketika seseorang mencapai usia akil baligh hingga sekitar usia 25 tahun. Ini merupakan fase penting ketika individu mulai menggunakan akalnya untuk mencari dan memahami kebenaran hakiki tentang kehidupan, Tuhan, dan tujuan eksistensinya.
Selanjutnya, fase ketiga adalah masa pasang-surut keimanan dan ketaatan, yang terjadi antara usia 25 hingga 40 tahun. Pada tahap ini, manusia dihadapkan pada berbagai ujian kehidupan: karier, keluarga, tanggung jawab sosial, dan godaan duniawi, yang sering kali memengaruhi kualitas keimanan dan konsistensi dalam beribadah. Masa ini merupakan fase krusial dalam menentukan arah spiritual seseorang. Terakhir, fase keempat adalah masa istiqomah, yang dimulai ketika seseorang menginjak usia 40 tahun. Di sinilah seseorang mulai menapaki kemantapan hidup spiritualnya—apakah ia akan istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, atau justru istiqomah dalam kelalaian dan kemaksiatan. Dalam Islam, usia 40 tahun disebut sebagai usia kematangan akal dan spiritual, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ahqaf: 15), yang menandai titik balik dalam perjalanan iman seseorang.
وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ .
Pendapat ini sejalan dengan pakar muslim, di antaranya:
1. Al-Ghazali (1058–1111 M) – Ulama & Filsuf Islam
Al-Ghazali dalam berbagai karyanya, terutama Iḥyāʾ ‘Ulūm ad-Dīn, menyebut bahwa perkembangan ruhani manusia berlangsung secara bertahap, dimulai dari:
- Fase nafsu ammarah (jiwa yang condong pada keburukan)
- Fase nafsu lawwamah (jiwa yang menyesali kesalahan)
- Fase nafsu muthmainnah (jiwa yang tenang dan tunduk pada kebenaran)
Masing-masing fase ini bisa dikaitkan dengan usia dan tingkat kematangan spiritual seseorang. Menurut Al-Ghazali, kedewasaan spiritual memuncak ketika seseorang sudah mampu menyadari hakikat dirinya dan hubungannya dengan Allah, biasanya dicapai pada usia dewasa setelah mengalami berbagai ujian kehidupan.
2. Ibn Sina (980–1037 M) – Filsuf dan Ilmuwan Muslim
Ibn Sina dalam karyanya tentang pendidikan dan perkembangan jiwa, membagi fase hidup manusia dalam kaitannya dengan pendidikan dan pembentukan akhlak:
- Usia anak: fokus pada penanaman nilai dasar dan akhlak.
- Usia remaja-dewasa awal: masa pencarian jati diri dan kebenaran.
- Usia dewasa: masa penerapan ilmu, tanggung jawab sosial, dan ujian hidup.
- Usia matang: masa puncak kesadaran filosofis dan spiritual.
3. Erik Erikson (1902–1994) – Psikolog Perkembangan Barat
Dalam Theory of Psychosocial Development, Erikson mengemukakan bahwa manusia mengalami krisis psikososial di setiap tahap usia yang mendorong pembentukan identitas dan nilai.
- Usia remaja (12–20): krisis identitas vs kebingungan – sejalan dengan "mencari kebenaran".
- Usia dewasa awal (20–40): krisis keintiman vs isolasi – fase ujian sosial dan emosional.
- Usia matang (40+): krisis integritas vs keputusasaan – refleksi hidup dan kebutuhan makna, yang banyak orang cari melalui iman atau spiritualitas.
Meskipun Erikson tidak membahas Tuhan secara langsung, pencarian makna dalam fase dewasa akhir sering kali mengarah pada dimensi spiritual atau religius.
4. Sayyid Quthb dan Fazlur Rahman (Cendekiawan Muslim Modern)
- Sayyid Quthb dalam Fi Dzilal al-Qur’an menekankan pentingnya kesadaran iman yang berproses seiring kematangan akal dan pengalaman hidup.
- Fazlur Rahman menekankan bahwa pertumbuhan etika
dan spiritual dalam Islam bersifat bertahap dan integral dengan
perkembangan akal dan tanggung jawab sosial.
Kaidah dalam menjaga Keistiqomahan
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ .
Menjaga istiqomah dalam kebaikan adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan, namun Allah menjanjikan kemudahan bagi siapa pun yang dengan tulus menempuh jalan takwa. Seseorang yang senantiasa istiqomah—berusaha memberi, bertakwa, dan membenarkan janji Allah—akan dipermudah langkahnya menuju kebaikan. Allah melapangkan jalannya, menjadikan amalnya ringan, dan meneguhkan hatinya dalam iman. Sebaliknya, siapa yang berpaling dari kebenaran, enggan berbuat baik, serta mendustakan balasan Allah, maka jalan hidupnya akan terasa berat dan penuh kesulitan. Ia akan menemukan diri terjerat dalam kelalaian dan kegelisahan yang terus-menerus. Inilah sunnatullah dalam kehidupan: bahwa istiqomah dibalas dengan kemudahan, dan penyimpangan dari jalan Allah dibalas dengan kesempitan.
Menutup dari tulisan ini, Abu Yazid al-Bistami mengatakan bahwa apapun balasan dari amal perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, namun istiqomah adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan sebagai balasan. Oleh karena itu, jangan tukar ketaatan kita dengan angan dan harapan yang bersifat dunia, misalnya beribadah dengan harapan agar kaya, banyak harta, dan keserbacukupan lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam hal dakwah dan kebaikan hingga akhir hayat. Aaamin.









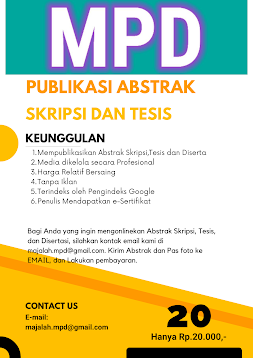









0 Komentar
Silakan tinggalkan komentar Anda