Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini bukan sekadar deklarasi normatif, melainkan janji konstitusional bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, menjunjung keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam praktik ketatanegaraan mutakhir, muncul pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sungguh menegakkan rule of law, atau justru bergerak ke arah rule by law?
Secara konseptual, rule of law menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan. A.V. Dicey menekankan tiga unsur utama, yakni supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan perlindungan hak-hak individu melalui peradilan yang independen. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sebaliknya, rule by law menjadikan hukum semata sebagai alat kekuasaan dibentuk dan ditegakkan bukan untuk membatasi kekuasaan, melainkan untuk melanggengkannya. Perbedaannya mungkin tipis dalam rumusan norma, tetapi sangat kontras dalam praktik ketatanegaraan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan rule by law tampak semakin menguat. Hal ini tercermin dari lahirnya berbagai regulasi strategis melalui proses legislasi yang minim partisipasi publik sebagaimana diamanatkan oleh prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas mensyaratkan asas keterbukaan, kejelasan tujuan, dan partisipasi masyarakat. Ketika regulasi dibentuk secara tergesa-gesa dan tertutup, hukum kehilangan legitimasinya sebagai hasil kehendak rakyat dan berubah menjadi instrumen kebijakan sepihak. Fenomena tersebut diperparah ketika hukum digunakan untuk merespons kritik publik secara represif. Padahal, kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks rule of law, hukum seharusnya melindungi ruang kebebasan sipil. Namun, dalam kerangka rule by law, hukum justru berpotensi dijadikan alat pembatas kebebasan dengan dalih ketertiban dan stabilitas.
Lebih jauh, relasi antara hukum dan kekuasaan menunjukkan gejala asimetris. Penegakan hukum kerap dinilai “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Prinsip equality before the law yang dijamin konstitusi dan menjadi ruh negara hukum kehilangan makna substantif ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan imparsial. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai penjaga keadilan sosial, melainkan sebagai mekanisme selektif yang cenderung melindungi kelompok berkuasa. Kondisi tersebut diperburuk oleh melemahnya etika konstitusional (constitutional morality). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi tidak cukup dipahami sebagai teks hukum, melainkan harus dihidupi sebagai nilai. Penyelenggara negara tidak hanya dituntut taat secara formal terhadap undang-undang, tetapi juga setia pada semangat keadilan, kepatutan, dan kepentingan umum. Ketika etika konstitusional diabaikan, produk hukum yang sah secara prosedural dapat kehilangan legitimasi secara moral dan substantif.
Peran lembaga-lembaga negara dalam sistem checks and balances pun patut dikritisi. Secara normatif, UUD 1945 telah merancang mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan. Namun, ketika fungsi pengawasan melemah dan relasi antarlembaga cenderung kompromistis dan transaksional, hukum kehilangan daya korektifnya. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi berisiko tereduksi menjadi bagian dari dinamika politik praktis. Pada titik ini, pertaruhan ketatanegaraan bukan lagi soal ada atau tidaknya hukum, melainkan bagaimana hukum digunakan. Negara yang dipenuhi regulasi belum tentu mencerminkan rule of law.
Justru, hiper-regulasi dapat menjadi indikator dominasi rule by law apabila hukum diproduksi tanpa orientasi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Mengembalikan rule of law ke rel konstitusionalnya membutuhkan lebih dari sekadar pembaruan norma hukum. Diperlukan penguatan budaya hukum, partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, serta keberanian lembaga negara untuk menempatkan konstitusi di atas kepentingan kekuasaan jangka pendek. Hukum harus kembali difungsikan sebagai alat pembatas kekuasaan (limitation of power), bukan sebagai perpanjangannya. Pada akhirnya, masa depan ketatanegaraan Indonesia sangat ditentukan oleh pilihan mendasar ini, apakah hukum akan terus dijadikan alat legitimasi kekuasaan, atau benar-benar ditegakkan sebagai fondasi keadilan dan demokrasi. Rule of law bukan sekadar konsep teoritis, melainkan prasyarat utama bagi negara hukum yang berkeadaban. Tanpa komitmen nyata terhadap prinsip tersebut, negara hukum berisiko tereduksi menjadi slogan kosong dalam praktik ketatanegaraan kita.









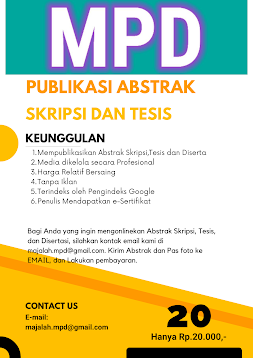









0 Komentar
Silakan tinggalkan komentar Anda